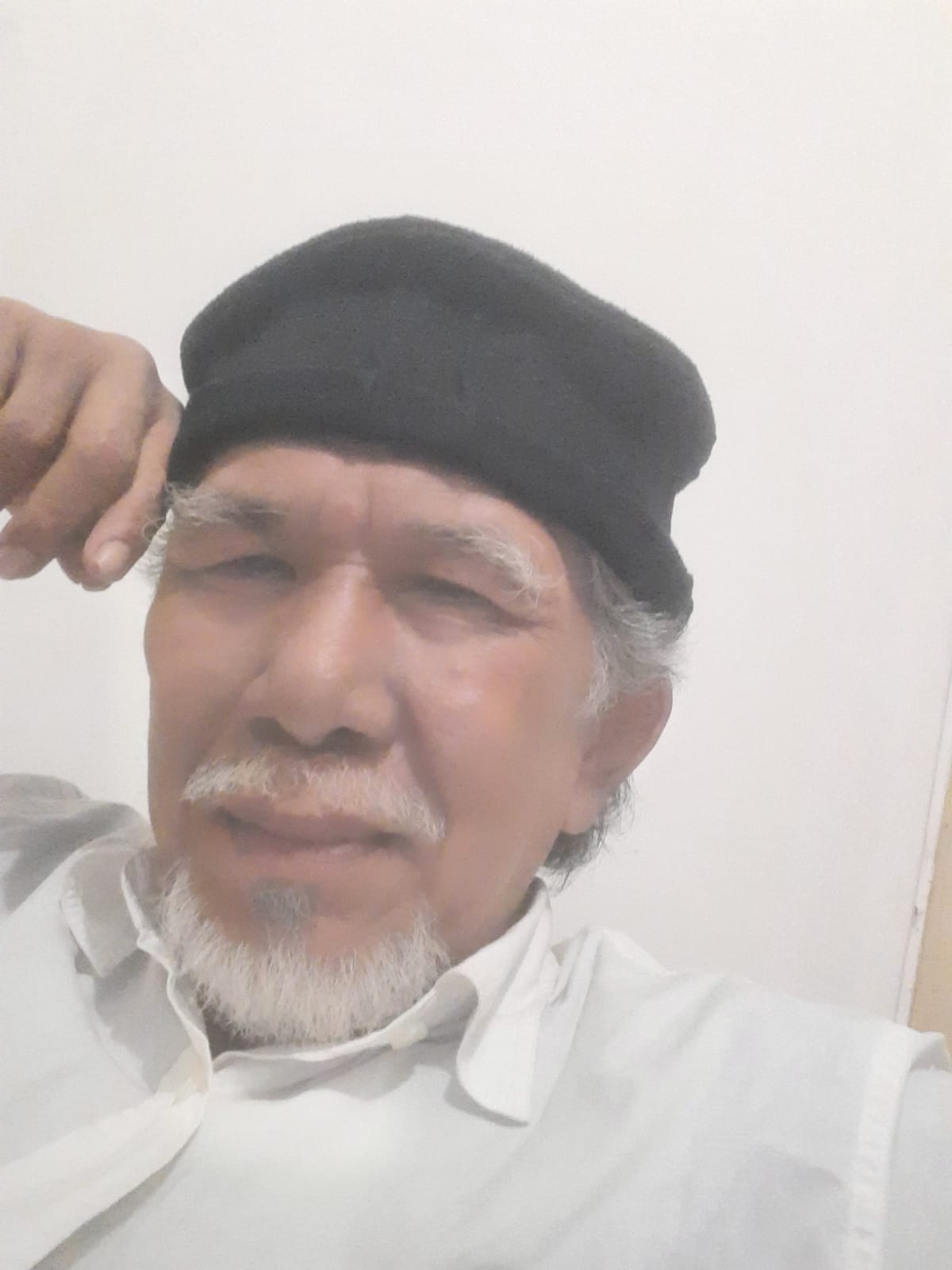Oleh MS.Tjik.NG
*Bismillahirrahmanirrahim*
Abstrak
Kritik publik terhadap alokasi anggaran konsumsi rapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tangerang Selatan (Tangsel) memperlihatkan ketegangan antara kewenangan anggaran pemerintah daerah dan hak warga negara untuk mengawasi.
Kasus yang disorot oleh Leony Vitria, mantan penyanyi cilik di mana anggaran konsumsi rapat tahun 2024 disebut mencapai Rp 60 miliar atau lebih, membuka ruang diskusi publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Artikel ini menganalisis latar belakang kritik tersebut, respons pemerintah, kerangka teoritis transparansi‐ akuntabilitas, mekanisme kontrol publik, tantangan implementasi, dan rekomendasi guna memperkuat pengawasan warga terhadap LKPD.
Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun secara formal pemerintah daerah telah mempublikasikan LKPD dan telah diaudit BPK, masih ada kesenjangan partisipatif dan pencerahan publik agar kontrol sosial dapat berjalan efektif.
Kata kunci: transparansi, akuntabilitas publik, LKPD, kontrol sosial, anggaran publik, kritik Leony Vitria
Latar Belakang
Pengelolaan keuangan publik adalah ujung tombak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Setiap rupiah yang dianggarkan semestinya memberi nilai langsung bagi kesejahteraan warga—melalui pelayanan dasar, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Namun dalam praktik, terdapat pos-pos belanja yang sering dianggap “seremonial”, “atmosfer birokrasi”, atau bahkan “boros”, yang memancing kritik publik.
Salah satu contoh paling menonjol baru-baru ini adalah kritik Leony Vitria terhadap anggaran konsumsi rapat di Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel).
Dalam unggahannya, Leony menyebut bahwa anggaran konsumsi rapat 2024 mencapai sekitar Rp 60 miliar (atau lebih kalau dihitung semua OPD). Angka ini kemudian memicu reaksi publik dan tanggapan dari Pemkot Tangsel, termasuk klaim bahwa seluruh anggaran sudah diaudit dan tersedia secara terbuka.
Kritik tersebut sebenarnya lebih luas: bukan sekadar soal angka besar, tetapi soal hak publik untuk mendapatkan informasi yang jelas, rinci, dan kontekstual agar masyarakat bisa memahami apakah anggaran yang dibelanjakan masuk akal atau tidak, dan menilai kinerja penyelenggara pemerintah.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mencoba menjawab:
1.Apa dasar kritikan Leony Vitria terhadap anggaran konsumsi rapat di Tangsel?
2 Bagaimana respons dan legitimasi dari Pemkot Tangsel terkait kritik tersebut?
3.Bagaimana kerangka teoritis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan LKPD yang memungkinkan publik ikut memantau?
4.Apa tantangan implementasi transparansi & akuntabilitas di tingkat daerah?
5.Apa rekomendasi agar kontrol publik terhadap LKPD bisa lebih efektif?
Tujuan Penulisan
Mengurai kasus konkret kritik publik sebagai ilustrasi dinamika pengawasan keuangan publik.
Menyajikan kerangka teoritis & empiris tentang transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik.
Memberi rekomendasi kebijakan agar partisipasi publik dalam pengawasan LKPD dapat diperkuat.
Metodologi
Artikel ini bersifat analisis kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari:
Laporan media (CNN Indonesia, Detik, Tirto) tentang kasus Leony vs Pemkot Tangsel.
Dokumen LKPD & catatan realisasi belanja (yang dipublikasikan Pemkot Tangsel).
Literatur akademik, jurnal, dan penelitian tentang transparansi & akuntabilitas pemerintah daerah.
Kritik Leony Vitria: Angka, Sorotan & Konteks
Apa yang dikritik
Beberapa poin utama yang menjadi sorotan publik melalui Leony:
Anggaran konsumsi rapat / makan-minum: angka sekitar Rp 60,29 miliar untuk rapat dan pos “jamuan/kunjungan” naik dari Rp 50,07 miliar ke Rp 60,29 miliar.
Anggaran jamuan tamu: naik menjadi Rp 7,22 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Belanja konsumsi total OPD: dalam beberapa laporan disebut mencapai Rp 66 miliar, tersebar hampir ke semua perangkat daerah.
Belanja perjalanan dinas pejabat: dikritisi dalam salah satu unggahan Leony, total dana perjalanan dinas pejabat di Pemkot Tangsel disebut mencapai Rp 117 miliar.
Belanja pakaian (seragam, dsb.): juga muncul sebagai pos kecil namun dipertanyakan urgensinya dalam konteks kebutuhan publik.
Leony menyatakan bahwa belanja‐belanja tersebut terkesan prioritas birokrasi dan bukan kebutuhan mendesak warga. Dalam unggahannya ia menulis:
_“Perjalanan dinas mereka … sampai Rp 117 miliar … jadi kalau kaya gini nih pajak dari rakyat untuk rakyat enggak ya?”_
-888-
Postingan tersebut viral, menarik ribuan interaksi media sosial dan menjadi bahan perbincangan publik.
Respons Pemerintah Daerah Tangsel
Pemerintah kota (Wali Kota & Pemkot Tangsel) merespons beberapa sorotan tersebut:
1.Audit & Opini BPK
Pemkot menyatakan bahwa anggaran yang dikritisi sudah diuji oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga dianggap sudah memenuhi standar penyajian laporan keuangan.
2.Publikasi LKPD
Pemkot menyebut bahwa LKPD telah dipublikasikan sejak 2019, termasuk dokumen pendukung, sehingga publik sebenarnya bisa mengakses data dasar.
3.Penjelasan sifat anggaran konsumsi sebagai agregat
Wali Kota menyebut bahwa pos konsumsi bukan hanya untuk rapat walikota, melainkan tersebar di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mencakup rapat internal, sosialisasi, pelatihan, kunjungan, dan jamuan tamu.
4.Pengawasan internal & eksternal
Pemkot menyatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh DPRD, Inspektorat, BPKP, dan melalui forum konsultasi publik. Semua penggunaan anggaran diklaim berada di bawah pengawasan ketat.
-888-
Meskipun demikian, publik tetap mempertanyakan rincian: misalnya, berapa banyak rapat, siapa peserta, apakah konsumsi itu proporsional, apakah ada pemborosan di OPD-OPD kecil, dsb.
Kekuatan & Batas Respons
Kekuatan: Respons pemerintah yang menyebut audit BPK dan opini WTP memberikan legitimasi formal bahwa laporan keuangan dianggap sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Keterbatasan: Legitimasi formal tidak otomatis menjawab keberatan publik bila detail penggunaan anggaran tidak dijelaskan secara rinci atau kontekstual. Publik tidak selalu paham interpretasi opini audit atau arbitrase teknis akuntansi.
Kasus ini menunjukkan bahwa legitimasi formal (audit, opini auditor) dan legitimasi sosial (kepercayaan publik) bisa berbeda.
Transparansi & Akuntabilitas dalam Pengelolaan LKPD
Untuk menilai peran publik dalam pengawasan LKPD, kita perlu memahami teori, regulasi, dan praktik transparansi & akuntabilitas dalam sektor publik.
Kerangka Teoritis
1.Teori Keagenan (Agency Theory)
Pemerintah daerah bertindak sebagai “agensi” yang dipercayakan warga sebagai “prinsipal”. Karena informasi asimetris (pemerintah punya akses data lebih banyak), publik bergantung pada informasi yang disediakan pemerintah agar bisa menilai kinerjanya.
2.Good Governance & Prinsip Transparansi
Transparansi adalah salah satu pilar tata kelola yang baik (good governance). Tanpa transparansi, akuntabilitas sulit ditegakkan. Dalam konteks keuangan publik, transparansi berarti menyediakan data anggaran & realisasi yang dapat diakses publik.
3.Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas berarti bahwa pihak yang diberi wewenang kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka. Dalam konteks publik, itu berarti pemerintah harus menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana anggaran digunakan serta konsekuensi realnya kepada warga.
4.Kontrol Sosial & Partisipasi Publik
Kritik, pengawasan, masukan warga dianggap elemen kontrol sosial yang memperkuat akuntabilitas. Tanpa partisipasi, transparansi tidak cukup karena informasi saja tidak menjamin perubahan.
5.Pengungkapan (Disclosure) dan Kualitas Laporan
Kualitas pengungkapan dalam LKPD seperti detail belanja, catatan atas laporan keuangan, penjelasan kebijakan akuntansi menentukan sejauh mana publik bisa memahami realisasi.
Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, semakin rendah tingkat korupsi. Misalnya:
Khairudin & Erlanda (2016) dalam studi pada kota-kota di Sumatera menemukan bahwa transparansi negatif berpengaruh terhadap korupsi, dan akuntabilitas positif berpengaruh terhadap korupsi.
Juliyanti (2023) menunjukkan bahwa pengungkapan LKPD memiliki pengaruh langsung terhadap akuntabilitas publik.
Khikmah & Purwanto (2023) menemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan fairness pada LKPD berpengaruh terhadap upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah di Pulau Jawa.
Jurnal‐jurnal lain juga menekankan bahwa kualitas LKPD (termasuk pengungkapan naratif, catatan, penjelasan selisih) sangat penting agar publik punya gambaran yang memadai.
Regulasi & Kewajiban Publikasi
Beberapa aturan yang mengatur transparansi & akuntabilitas LKPD:
UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan lembaga publik, termasuk pemerintah daerah, untuk memberikan akses informasi ke publik.
UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah — menetapkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa LKPD harus disusun, diaudit, dan dipublikasikan.
Peraturan BPK, Permendagri, dan standar SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) menuntut format, struktur, catatan atas laporan, dan pengungkapan tertentu agar laporan keuangan daerah memenuhi standar teknis dan transparan.
Dengan kerangka tersebut, kritik publik terhadap anggaran rapat Rp 60 miliar bukan hanya “suara kosong”, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang seharusnya dijamin oleh sistem demokrasi & regulasi.
-888-
Mekanisme & Peran Publik dalam Monitoring LKPD
Untuk agar hak publik tidak hanya retorika, tetapi nyata, maka ada mekanisme dan praktik yang bisa diperkuat. Berikut mekanisme yang sudah ada dan idealnya ditingkatkan:
Mekanisme yang Ada
1.Publikasi LKPD & dokumen pendukung
Pemerintah daerah umumnya mengunggah LKPD tahunan dan laporan pendukung di situs resmi, portal keuangan daerah, atau melalui media publik.
2.Audit BPK & opini audit
Setelah LKPD disusun, BPK melakukan pemeriksaan dan memberikan opini (WTP, WDP, TMP, dsb.). Ini adalah pengesahan formal atas kelayakan laporan.
3.DPRD daerah sebagai wakil publik
DPRD memiliki fungsi pengawasan anggaran dan meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah.
4.Inspektorat / APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
Unit internal pemerintahan yang melakukan audit internal dan pengawasan penggunaan anggaran.
5 Forum publik & konsultasi.
Forum musrenbang, rapat dengar pendapat, hearing DPRD bersama pemerintah daerah memberikan ruang publik untuk masukan.
6.Media & masyarakat sipil
Media lokal atau organisasi masyarakat sipil (LSM) dapat mengakses LKPD, menganalisis, lalu menyebarkan ke publik agar kontrol sosial berjalan.
Hambatan & Tantangan
Meskipun mekanisme telah ada, dalam kenyataan praktiknya terdapat hambatan:
1.Ketidakjelasan / keterbatasan detail pengungkapan
LKPD mungkin memuat angka agregat tanpa rincian (misalnya: “konsumsi” senilai x miliar tanpa uraian OPD, jenis kegiatan, jumlah peserta).
2.Bahasa teknis & sulit dipahami publik awam
Istilah akuntansi, singkatan, catatan atas laporan sering membingungkan masyarakat awam.
3.Durasi publikasi & keterlambatan.
Jika LKPD dipublikasikan sangat telat, atau dokumen pendukung tidak lengkap, maka masyarakat kehilangan momentum untuk mengkritik.
4.Keterbatasan akses digital / literasi informasi
Tidak semua warga memiliki akses internet atau kemampuan membaca dokumen keuangan.
5.Perlawanan birokrasi & budaya tertutup
Pejabat daerah bisa enggan mengungkapkan rincian karena takut dikritik atau dianggap tidak kompeten.
6 Sanksi lemah terhadap penyalahgunaan
Bila audit menemukan kejanggalan, proses penegakan hukum atau sanksi administratif bisa lambat atau tidak efektif.
7.Fragmentasi pengawasan
Pemerintah pusat, daerah, DPRD, BPK, media, masyarakat masing-masing punya fungsi kontrol, tetapi koordinasi antar mereka sering lemah.
Dalam konteks kasus Tangsel, sebagian kritik publik menunjukkan bahwa meski LKPD “diumumkan”, detail pos konsumsi di OPD kecil mungkin tidak mudah diakses atau dibandingkan, sehingga publik hanya melihat “angka besar” tanpa konteks yang memadai.
-888-
Analisis: Sejauh Mana Hak Publik Memantau LKPD Terwujud?
Dengan landasan teoritis dan praktik di atas, kita bisa menganalisis kasus Tangsel sebagai contoh konkret.
Kekuatan dalam Kasus Tangsel
Keterbukaan formal: Pemkot mengklaim LKPD telah dipublikasikan sejak 2019, dan bahwa audit oleh BPK telah dilakukan.
Respon instansi publik: Dengan adanya klarifikasi publik dari Wali Kota dan Pemkot, warganya memiliki ruang mendengar jawaban resmi.
Pemberdayaan media & publik: Kritik Leony mendapat perhatian luas media dan publik, memperluas ruang diskusi dan tekanan sosial terhadap pemerintah daerah.
Kelemahan / Kekurangan
Kurangnya rincian & narasi penjelasan: Meskipun angka konsumsi disebut, penjelasan mendasar (seperti jenis rapat, jumlah peserta, frekuensi, standar konsumsi) belum diumumkan secara detail publik.
Asimetri informasi tetap besar: Warga biasa tidak punya kemampuan teknis mengurai catatan keuangan di LKPD agar dapat mengevaluasi apakah suatu belanja proporsional atau berlebihan.
Opini audit tidak cukup meyakinkan bagi publik: BPK bisa memberikan opini WTP, tetapi publik mungkin tetap mencurigai bahwa pengeluaran yang sah secara formal belum tentu efisien atau relevan.
Respon pemerintah kadang defensif: Fokus pada legitimasi formal (audit, opini) bisa menutupi dialog terbuka soal perbaikan sistem transparansi.
Kurangnya mekanisme interaktif: Misalnya, dashboard interaktif di situs Pemkot dengan filter OPD, kategori belanja, periode, dan visualisasi realisasi vs anggaran sangat jarang tersedia atau mudah diakses.
Implikasi terhadap Hak Publik
Kasus ini menunjukkan bahwa publik memang memiliki hak untuk memantau dan mengkritisi LKPD — hal itu didukung regulasi dan kebiasaan demokrasi. Namun hak itu tidak secara otomatis diterjemahkan dalam kemampuan efektif tanpa dukungan sistem informasi yang terbuka, edukasi publik literasi keuangan, dan komitmen pemerintah terhadap dialog terbuka.
Ketika publik hanya melihat “angka besar” tanpa latar cerita, kritik bisa dianggap emosional atau politik. Tapi itu juga menunjukkan bahwa pemerintah belum menyediakan ruang transparansi yang memadai agar warga bisa memahami dan berdialog secara rasional.
Rekomendasi Kebijakan & Praktek
Agar hak publik untuk memantau, mengkritisi, dan memberikan masukan atas LKPD benar-benar berjalan, berikut rekomendasi strategis:
1.Sistem Dashboard Keuangan Interaktif
Pemerintah daerah harus menyediakan portal keuangan interaktif yang memungkinkan publik menjelajahi data:
Filter berdasarkan OPD, jenis belanja, jenis kegiatan (konsumsi, modal, perjalanan, pelatihan), periode triwulan, dan realisasi vs anggaran.
Visualisasi grafik & peta agar warga bisa cepat memahami pos mana yang tinggi.
Penjelasan naratif minimal: misalnya, “pos konsumsi OPD X untuk rapat dengan peserta Y orang, standar konsumsi per orang Z ribu”.
2.Rincian & Catatan Atas Laporan yang Lebih Terbuka
LKPD harus disertai catatan atas laporan keuangan yang mudah dipahami, dengan:
Penjabaran kegiatan yang termasuk dalam “konsumsi”, “jamuan”, “pelatihan / sosialisasi”.
Justifikasi standar (misalnya tarif konsumsi per orang, frekuensi rapat) berdasarkan pedoman baku.
Penjelasan selisih antara anggaran dan realisasi, termasuk penyebab utama over/under realisasi.
3.Literasi Keuangan Publik & Edukasi
Pemerintah atau lembaga masyarakat sipil perlu menyelenggarakan workshop, modul daring, infografik yang menjelaskan cara membaca LKPD kepada masyarakat awam.
Media lokal bisa memfasilitasi interpretasi LKPD lewat rubrik “Membaca LKPD” atau “Belanja OPD dijabarkan”.
4.Forum Musyawarah & Public Hearing yang Terstruktur
Sebelum RAPBD disahkan, forum publik (musrenbang, dialog OPD) harus diprioritaskan agar warga bisa memberi masukan terhadap rancangan anggaran.
Setelah LKPD disusun, pemerintah dapat menyelenggarakan hearing publik: memaparkan realisasi anggaran dan menerima pertanyaan masyarakat.
DPRD juga harus memfasilitasi “DPRD menjelaskan LKPD ke publik” — bukan hanya rapat internal.
5 Penguatan Inspektorat & Audit Kinerja Independen
Inspektorat daerah harus diberikan kapasitas dan independensi agar bisa menindak temuan penggunaan anggaran yang tidak rasional atau berlebihan.
Lembaga audit independen atau masyarakat sipil bisa diberi akses untuk audit kinerja pos tertentu sebagai audit partisipatif.
6.Penegakan Sanksi & Tindak Lanjut
Apabila audit menemukan penyimpangan (anggaran konsumsi terlalu tinggi tanpa basis standar, atau penyalahgunaan), harus ada audit tindak lanjut dan sanksi administratif yang transparan ke publik.
Hasil audit dan rekomendasi peninjauan harus diterbitkan dan dipublikasikan, termasuk status tindak lanjutnya.
7 Kolaborasi dengan Media & Masyarakat Sipil
LSM, jurnal publik, media lokal bisa dijadikan mitra pemerintah dalam melakukan data journalism terhadap LKPD dan menyebarluaskan temuan ke masyarakat luas.
Pemerintah bisa membentuk “open data challenge” atau kompetisi analisis data keuangan daerah agar warga lebih tertarik memeriksa LKPD.
8.Standar Nasional & Benchmark Perbandingan Antar Daerah
Pemerintah pusat atau Kementerian Dalam Negeri bisa menetapkan standar minimal pengungkapan (jenis belanja wajib dipecah ke level kegiatan) dan template nasional agar transparansi di tiap daerah bisa dibandingkan.
Publik atau lembaga penelitian bisa membuat indeks transparansi keuangan daerah dan menerbitkan ranking agar pemerintah memiliki tekanan kompetitif untuk lebih transparan.
Kesimpulan
Kritik Leony Vitria terhadap anggaran konsumsi rapat Rp 60 miliar di Tangsel lebih dari sekadar sorotan selebritas. Ia mencerminkan kebutuhan mendesak agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah tidak hanya formalitas, tetapi nyata—dapat dipahami warga, dipertanyakan warga, dan diperbaiki pemerintah.
Kasus ini memperlihatkan bahwa:
Publik memiliki hak untuk memantau, mengkritisi, dan meminta pertanggungjawaban atas LKPD, karena anggaran daerah berasal dari pajak warga.
Legitimasi formal (seperti opini WTP dari BPK) memang penting, tetapi bukan akhir cerita; publik tetap butuh akses ke rincian yang memadai agar bisa menilai efisiensi & relevansi.
Terdapat kesenjangan nyata antara transparansi formal dan efektivitas kontrol publik; hal ini disebabkan oleh keterbatasan detail pengungkapan, hambatan literasi, dan kurangnya mekanisme interaktif.
Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, pemerintah perlu membangun sistem transparansi yang interaktif, mendidik publik, membuka dialog terbuka, memperkuat pengawasan internal & eksternal, serta menjamin sanksi bila ditemukan penyalahgunaan.
Dengan rekomendasi kebijakan di atas, harapannya hak publik untuk memantau dan mengkritisi LKPD bisa menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan daerah yang sehat, efisien, dan akuntabel.
والله اعلم بالصواب
C24092025, Tabik 🙏
Referensi :
1. Khairudin, K., & Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Kota se-Sumatera). Jurnal …
2. Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. Reviu Akuntansi, Manajemen & Bisnis, 3(1).
3. Khikmah, L., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Pencegahan Korupsi (Studi Empiris di Pulau Jawa). Diponegoro Journal of Accounting, 12(1).
4. Sihombing, P. R., et al. (2020). Pengaruh Transparansi, LKPD dan PAD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. E-Journal BSI.
5. “Leony Kritik Anggaran Pemkot Tangsel: Konsumsi Rapat Rp60 Miliar” CNN Indonesia.
6. “Anggaran Makan-Minum Rp 66 M Disentil Leony, Walkot Tangsel Buka Suara” Detik News.
7. “Pemkot Tangsel Respons Leony soal Dana Perjalanan Dinas Rp117 M” Tirto.
8. Artikel “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik” Jurnal Bisnis & Manajemen West Science.
9. “Cerminan Transparansi dan Akuntabilitas” e-Jurnal Akmen.
10. Artikel “Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan …” Jurnal UNSAM.
11. Artikel “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan …” Jurnal MEA (Ilmu & Riset Akuntansi).
12. Artikel “PENGARUH TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN …” Jurnal JENSI