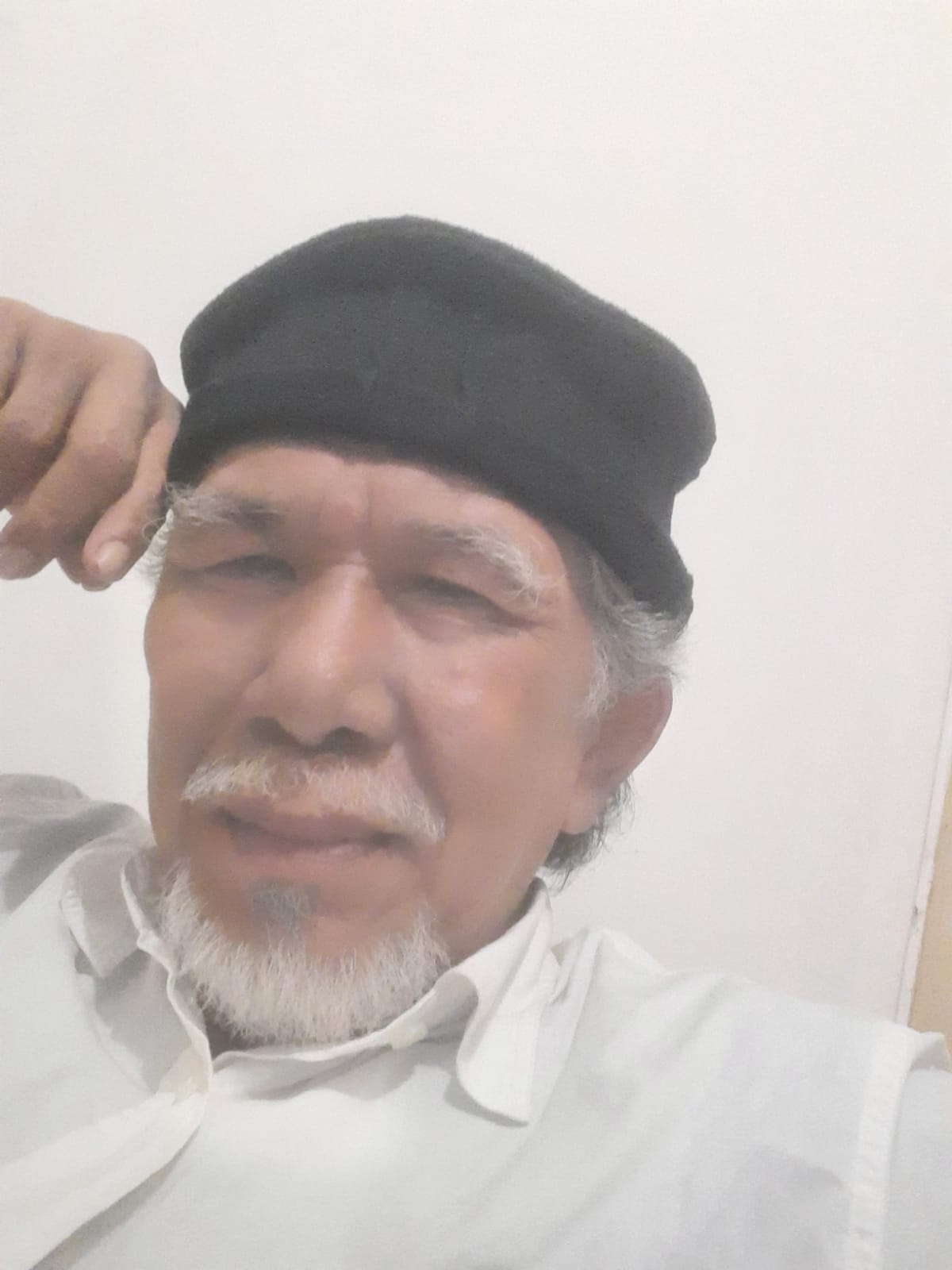Oleh MS.Tjik.NG
_*Bismillahirrahmanirrahim*_
Pendahuluan
Sejarah bangsa Indonesia penuh dengan kisah dramatis tentang tokoh-tokohnya, baik yang menjadi pahlawan maupun yang menjadi korban dinamika politik. Dua di antaranya adalah Soekarno, proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia, dan Buya HAMKA, ulama besar, sastrawan, serta pemimpin umat.
Hubungan antara keduanya tidak selalu harmonis. Dalam periode akhir kekuasaan Soekarno, Buya HAMKA sempat dipenjarakan tanpa diadili. Tuduhan politik dijatuhkan kepadanya, meskipun tidak pernah terbukti secara hukum.
Namun, sejarah mencatat bahwa ketika Soekarno wafat pada tahun 1970, beliau berwasiat agar jenazahnya disalatkan oleh HAMKA. Sebuah ironi sejarah sekaligus teladan luar biasa tentang keikhlasan, pemaafan, dan kebesaran jiwa.
Tulisan ini akan membahas latar belakang konflik, penahanan HAMKA, karya-karyanya di balik jeruji, hingga momen menggetarkan ketika ia menyalatkan jenazah Soekarno. Lebih jauh, tulisan ini hendak menyoroti makna moral, religius, dan historis dari peristiwa tersebut bagi generasi kini.
-888-
Sosok Buya HAMKA
HAMKA lahir di Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908, dengan nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia anak dari ulama besar, Haji Rasul, seorang pembaharu Islam di Minangkabau.
Sejak kecil HAMKA dikenal gemar membaca, belajar agama, dan menulis. Karyanya tersebar dalam bentuk novel, esai, hingga karya tafsir. Beberapa novelnya seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijck dan Di Bawah Lindungan Ka’bah menjadikannya dikenal luas sebagai sastrawan Muslim.
Namun di atas semua itu, kontribusinya yang paling monumental adalah Tafsir al-Azhar, sebuah tafsir Al-Qur’an 30 juz dalam bahasa Indonesia. Tafsir ini lahir dari penghayatan mendalam, ilmu yang luas, serta pengalaman spiritual yang matang termasuk ketika beliau berada dalam penjara.
HAMKA juga aktif di Muhammadiyah dan Partai Masyumi, sehingga kiprah politiknya tidak bisa dilepaskan dari perjalanannya sebagai ulama.
Ia menjadi suara kritis terhadap kebijakan Soekarno, terutama ketika Orde Lama semakin cenderung otoriter.
Penahanan HAMKA oleh Rezim Soekarno
Pada tahun 1964, rezim Soekarno menahan HAMKA dengan tuduhan terlibat gerakan politik yang dianggap hendak menjatuhkan pemerintah. Tuduhan itu tidak pernah dibuktikan di pengadilan.
Penahanan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Hampir dua tahun beliau dipenjara, hingga 1966. Selama di balik jeruji, HAMKA mengalami penderitaan lahir batin. Namun justru dalam kondisi itulah, ia menyelesaikan sebagian besar karyanya.
Banyak catatan sejarah menyebut, bila HAMKA tidak dipenjara, mungkin Tafsir al-Azhar tidak akan pernah lahir dalam bentuknya yang utuh.
Penjara yang dimaksudkan untuk meredam suaranya, justru menjadi ladang amal jariyah terbesar sepanjang hidupnya.
Hubungan Bung Karno dan HAMKA
Hubungan Soekarno dan HAMKA ibarat ombak yang pasang surut. Pada satu sisi, keduanya sama-sama nasionalis, sama-sama Muslim, dan sama-sama mencintai bangsa ini.
Namun pada sisi lain, perbedaan pandangan politik membuat mereka berseberangan.
Soekarno ingin mengokohkan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis), sedangkan HAMKA dengan keras menolak kompromi dengan komunisme. Hal inilah yang menimbulkan gesekan tajam.
Namun, di balik konflik politik, ada simpul pribadi yang tetap menghormati. Bung Karno memahami kapasitas HAMKA sebagai ulama, sementara HAMKA tetap menaruh hormat kepada Bung Karno sebagai presiden dan proklamator bangsa.
-888-
Wasiat Terakhir Bung Karno
Ketika sakit-sakitan menjelang akhir hayatnya, Bung Karno berpesan kepada keluarga: jika ia meninggal, mintalah HAMKA untuk memimpin salat jenazahnya. Wasiat ini mengejutkan banyak pihak.
Mengapa seorang presiden yang pernah memenjarakan seorang ulama, justru meminta ulama itu yang menyalatkannya? Pertanyaan itu masih menjadi bahan refleksi hingga kini.
Banyak yang menafsirkan, Bung Karno memiliki hubungan batin tersendiri dengan HAMKA. Ia tahu bahwa hanya doa tulus dari seorang ulama besar yang mampu mengiringi kepergiannya dengan penuh keberkahan.
Malam Kematian Bung Karno
Tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno wafat di Wisma Yaso, Jakarta. Kabar duka menyebar cepat. Para pejabat, tokoh bangsa, dan rakyat berdatangan untuk memberi penghormatan terakhir.
Keluarga kemudian menyampaikan wasiat Bung Karno kepada Buya HAMKA. Bagi HAMKA, ini bukan perkara ringan. Ia pernah merasakan pahitnya dizalimi, namun kini diminta menunaikan tugas mulia.
HAMKA dengan rendah hati menerima. Ia menanggalkan dendam, dan dengan keikhlasan berangkat menuju Wisma Yaso.
Prosesi Salat Jenazah di Wisma Yaso
Di ruangan itu, jenazah Bung Karno terbujur kaku. Air mata keluarga bercucuran, sementara suasana penuh keheningan.
HAMKA maju ke depan. Ia berdiri sebagai imam. Suaranya lantang namun lembut, memandu takbir demi takbir. Para pelayat mengikuti di belakang.
Di tengah bacaan doa, banyak yang terisak. Mereka tidak hanya menangisi kepergian seorang proklamator, tetapi juga tersentuh oleh pemandangan seorang ulama yang menanggalkan luka pribadi demi menjalankan amanah agama.
Kebesaran Jiwa HAMKA
Setelah prosesi selesai, ada yang bertanya kepada HAMKA: Bagaimana ia bisa ikhlas menyalatkan orang yang pernah memenjarakannya?
HAMKA menjawab dengan singkat namun dalam:
_”Saya memaafkan beliau. Justru karena beliau pernah menahan saya, saya bisa menulis Tafsir al-Azhar. Itu adalah karunia Allah.”_
Jawaban itu mencerminkan kebesaran jiwa seorang ulama: dendam diganti doa, luka diganti syukur, dan permusuhan diganti pengampunan.
Makna Religius dan Simbolik
Dalam Islam, memaafkan adalah akhlak mulia. Rasulullah ﷺ sendiri sering memberi teladan dengan memaafkan musuh-musuhnya. HAMKA hanya menghidupkan sunnah itu dalam konteks modern.
Peristiwa ini juga punya makna simbolik: bahwa agama dapat menjadi jembatan rekonsiliasi politik. Bahwa persatuan umat dan bangsa lebih penting daripada dendam pribadi.
HAMKA menyalatkan Bung Karno bukan hanya peristiwa agama, tetapi juga peristiwa sejarah yang mengajarkan bahwa pemaafan bisa menyembuhkan luka bangsa.
Reaksi Masyarakat
Banyak kalangan memuji sikap HAMKA sebagai teladan akhlak. Namun ada juga yang mengkritik, menganggap HAMKA seolah melupakan luka sejarah.
Namun, seiring waktu, mayoritas melihat peristiwa ini sebagai bukti kebesaran hati seorang ulama. Bahkan anak-anak Bung Karno sendiri kemudian selalu menaruh hormat kepada HAMKA.
Irfan Hamka, putra Buya, menulis dalam bukunya bahwa peristiwa itu menjadi salah satu momen paling menggetarkan dalam sejarah keluarganya.
-888-
Hikmah bagi Generasi Kini
Generasi sekarang bisa belajar bahwa politik selalu bisa melukai, tapi agama bisa menyembuhkan.
Kita bisa belajar dari HAMKA untuk menaruh masa lalu di belakang, lalu menatap masa depan dengan hati yang bersih. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa berdamai dengan sejarahnya sendiri.
Refleksi
Andai HAMKA menolak menyalatkan Bung Karno, mungkin tidak ada yang bisa menyalahkannya. Namun, ia memilih jalan sebaliknya: menjadi imam dengan penuh ikhlas.
Sikap ini menunjukkan bahwa kebesaran seseorang tidak terletak pada jabatannya, tetapi pada kelapangan hatinya.
Penutup
Peristiwa salat jenazah Bung Karno oleh Buya HAMKA adalah potret rekonsiliasi moral yang indah. Sejarah bangsa ini tidak hanya dibangun dengan politik dan kekuasaan, tetapi juga dengan doa, keikhlasan, dan akhlak mulia.
Generasi sekarang seharusnya meneladani semangat itu: membuang dendam, menumbuhkan maaf, dan menatap masa depan bersama.
C09092025 Tabik 🙏
Daftar Pustaka :
1. Irfan Hamka. Ayah… Kisah Buya HAMKA. Jakarta: Republika, 2013.
2. Hamka. Tafsir al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
3. Tempo.co. “Kisah Soekarno Minta Buya Hamka Menyalatkan Jenazahnya.”
4. Islami.co. “Kisah Buya Hamka Jadi Imam Salat Jenazah Bung Karno.”
5. Islampos.com. “Buya Hamka Menshalati Jenazah Bung Karno.”
6. Ensiklopedi Islam, Jilid 2.