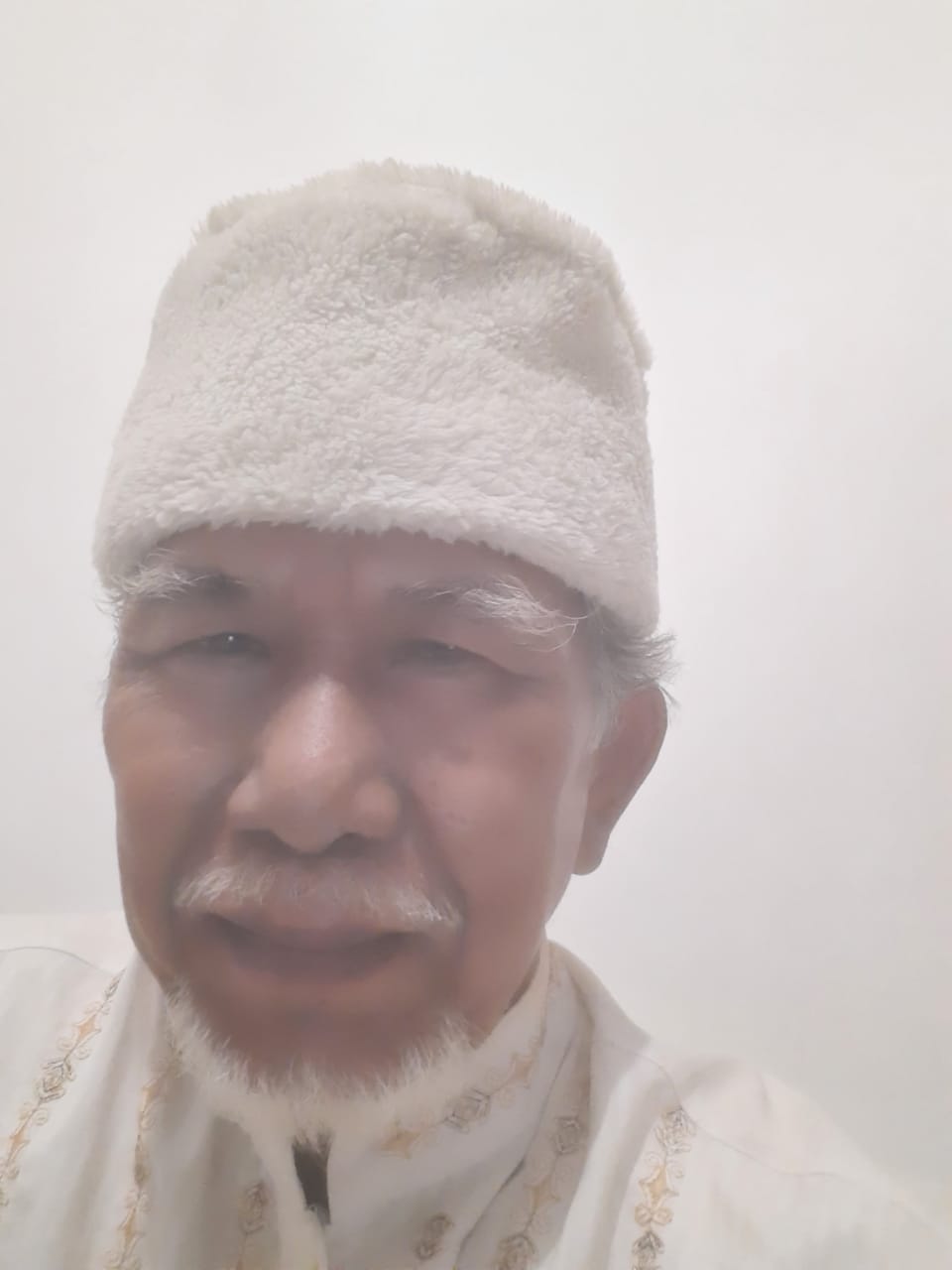MS.Tjik.NG
*Bismillahirrahmanirrahim*
Pendahuluan
Sampah merupakan problem klasik kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Pertumbuhan penduduk, pesatnya urbanisasi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menimbulkan konsekuensi serius berupa lonjakan produksi sampah yang kerap melampaui kapasitas pengelolaan.
Kota Tangsel, sebagai kota penyangga DKI Jakarta, menghadapi persoalan akut setelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang kewalahan menampung sampah yang setiap hari diproduksi.
Dalam situasi terdesak, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel mencari jalan keluar dengan menjalin kerja sama bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang untuk membuang sebagian sampah ke TPA Bongkonol. Akan tetapi, rencana ini menimbulkan kontroversi. Pemkab Pandeglang terbuka menerima kerja sama, namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sebagian besar masyarakat menolak dengan tegas.
Tulisan ini akan membahas krisis sampah Tangsel dari perspektif tata kelola lingkungan, politik lokal, serta keadilan ekologis. Fokus utama diarahkan pada dilema kebijakan lintas wilayah—bagaimana sebuah kota modern seperti Tangsel mencoba memindahkan beban sampahnya ke daerah lain, dan bagaimana daerah penerima menolak dengan alasan hak lingkungan, sosial, dan politik.
Krisis Sampah Kota-Kota Besar: Konteks Nasional dan Global
Krisis sampah bukan hanya problem Tangsel, melainkan fenomena global. Menurut laporan World Bank (2018) dalam What a Waste 2.0, jumlah produksi sampah dunia mencapai 2,01 miliar ton per tahun dan diproyeksikan meningkat hingga 3,4 miliar ton pada 2050. Sebagian besar sampah tersebut berasal dari wilayah perkotaan dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi.
Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa volume sampah nasional pada 2022 mencapai sekitar 68,5 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 65–70% yang terangkut ke TPA, sementara sisanya menumpuk di lingkungan. Kota-kota besar di Jabodetabek termasuk Tangsel adalah kontributor utama.
Kota Tangsel sendiri, dengan jumlah penduduk hampir 1,5 juta jiwa, memproduksi rata-rata 900 ton sampah per hari (BPS, 2023). Sementara kapasitas TPA Cipeucang hanya mampu menampung sebagian kecil, sehingga terjadi penumpukan dan bahkan longsor sampah pada 2020 yang menimbulkan pencemaran Sungai Cisadane (Kompas, 2020). Peristiwa tersebut menandai kegagalan tata kelola sampah Tangsel secara mandiri.
Kasus Tangsel dan TPA Cipeucang
TPA Cipeucang beroperasi sejak 2010 dengan luas lahan sekitar 9 hektare. Namun, sejak awal keberadaannya sudah diperkirakan hanya mampu menampung sampah dalam jangka waktu terbatas. Minimnya pengembangan teknologi pengolahan modern membuat TPA ini hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan akhir konvensional (open dumping), tanpa pengolahan memadai.
Pada 2020, longsornya gunungan sampah di Cipeucang ke Sungai Cisadane menjadi alarm keras. Peristiwa ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengganggu pasokan air baku untuk masyarakat di Tangerang Raya. Sejak saat itu, kapasitas Cipeucang semakin menurun drastis.
Untuk mengatasi darurat sampah, Pemkot Tangsel mengambil langkah darurat. Beberapa skema sempat dibicarakan, termasuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan kerja sama dengan daerah sekitar. Namun, hingga kini solusi permanen belum terealisasi.
Rencana Kerja Sama dengan Pandeglang
Pada 2025, Pemkot Tangsel berinisiatif menjalin kerja sama dengan Pemkab Pandeglang untuk membuang sebagian sampah ke TPA Bongkonol. Pandeglang, sebagai kabupaten dengan wilayah luas dan populasi lebih sedikit, dianggap mampu menampung limpahan sampah Tangsel.
Pemkab Pandeglang pada dasarnya terbuka dengan ide tersebut. Bagi pemerintah daerah, kerja sama lintas wilayah dapat berarti tambahan pemasukan daerah, serta peluang mempercepat pembangunan infrastruktur TPA. Pemkot Tangsel sendiri menjanjikan dukungan anggaran dalam bentuk retribusi serta kompensasi.
Namun, langkah ini segera menuai penolakan keras dari DPRD Pandeglang dan masyarakat setempat.
-888-
Resistensi DPRD dan Masyarakat
DPRD Pandeglang menolak rencana kerja sama tersebut dengan alasan menjaga kepentingan masyarakat dan lingkungan. Menurut mereka, Pandeglang tidak seharusnya dijadikan “tempat sampah” bagi kota lain. Penolakan ini sejalan dengan aspirasi warga sekitar TPA Bongkonol yang khawatir akan dampak pencemaran air tanah, bau, kesehatan, hingga menurunnya harga tanah.
Fenomena ini dapat dipahami dalam kerangka teori Not In My Backyard (NIMBY), di mana masyarakat menolak fasilitas publik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif meskipun fasilitas tersebut dianggap penting. NIMBY dalam kasus Pandeglang bukan sekadar soal ego lokal, melainkan cermin dari kesadaran hak ekologis masyarakat.
Kasus serupa juga terjadi di berbagai daerah lain. Misalnya, penolakan warga Bekasi terhadap sampah Jakarta yang dibuang ke Bantargebang, serta konflik antara Surabaya dan Sidoarjo soal pengelolaan sampah lintas batas. Semua menunjukkan problem mendasar: kota besar sering kali berusaha “mengekspor” masalahnya ke daerah lain.
Perspektif Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Ekologis
Dari sudut pandang tata kelola, persoalan ini memperlihatkan lemahnya manajemen lingkungan di tingkat lokal. Kota Tangsel yang memiliki APBD cukup besar semestinya mampu membangun sistem pengolahan mandiri berbasis circular economy. Namun, kenyataannya justru mencari jalan pintas dengan membuang ke daerah lain.
Konsep keadilan ekologis menegaskan bahwa beban lingkungan tidak boleh ditanggung sepihak oleh masyarakat tertentu. Dalam hal ini, Pandeglang sebagai daerah penerima justru menanggung dampak negatif dari konsumsi dan produksi sampah kota metropolitan.
Dalam kerangka hukum, UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur prinsip polluter pays, yakni pihak penghasil limbah harus bertanggung jawab.
Dengan demikian, secara normatif, Tangsel tidak bisa begitu saja memindahkan tanggung jawabnya kepada Pandeglang tanpa mekanisme kompensasi dan partisipasi masyarakat yang adil.
-888-
Alternatif Solusi
Untuk keluar dari dilema ini, ada beberapa alternatif solusi yang bisa ditempuh:
1.Penguatan Sistem Pengolahan Mandiri di Tangsel
Pemilahan sampah dari sumber.
Peningkatan fasilitas daur ulang.
Pemanfaatan teknologi maggot untuk sampah organik.
2.Pengembangan Teknologi Energi Terbarukan
Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan model waste-to-energy.
Refuse Derived Fuel (RDF) untuk suplai industri semen.
3.Kolaborasi Regional Jabodetabek
Membentuk badan khusus lintas daerah untuk pengelolaan sampah.
Skema berbagi biaya dan tanggung jawab, bukan sekadar “membuang ke daerah lain”.
4.Partisipasi Publik
Mengedukasi warga untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang (3R).
Mendorong keterlibatan komunitas dan sektor swasta.
Sudah sepantasnya Indonesia memiliki wadah permanen Non Departemen untuk pengelolaan sampah secara profrsional, seperti mendirikan “Badan Pengelola Sampah Nasional” (BPSN).
Atau minimal Ibu Kota Jakarta bersama daerah penyanggah (Jabotabek plus) membuat wadah bersama, misalnya Badan Pengelola Sampah Bersama . Dengan alokasi lintas anggaran boleh jadi mampu membuat atau membeli mesin canggih yang bisa menanggulangi persampahan sekaligus menghasil energi sampah.
Penutup
Kasus Tangsel–Pandeglang bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan sampah, melainkan refleksi dari tata kelola kota dan keadilan ekologis. Pemkot Tangsel menghadapi dilema besar: antara mencari solusi instan dengan memindahkan masalah ke daerah lain, atau membangun sistem pengelolaan mandiri yang berkelanjutan.
Penolakan DPRD dan masyarakat Pandeglang menunjukkan pentingnya partisipasi publik dalam setiap kebijakan lingkungan. Sebuah kota modern tidak bisa berdaulat hanya dengan membangun gedung pencakar langit dan kawasan elite, tetapi harus juga mampu mengelola limbahnya secara adil dan berkelanjutan.
Jika Tangsel berhasil mengatasi krisis sampah dengan inovasi dan tata kelola yang baik, hal itu bisa menjadi preseden positif bagi kota-kota lain di Indonesia.
Sebaliknya, jika jalan pintas dengan membuang ke Pandeglang dipaksakan, maka yang terjadi adalah ketidakadilan ekologis dan konflik sosial yang semakin tajam.
والله اعلم بالصواب
C19082025, Tabik🙏
Daftar Referensi
Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta: BPS RI.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional. Jakarta: KLHK.
Kompas. (2020). “Gunungan Sampah TPA Cipeucang Longsor, Sungai Cisadane Tercemar.” [Online].
Santosa, M.A. (2019). Politik Lingkungan dan Keadilan Ekologis di Indonesia. Jakarta: Pustaka Obor.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
World Bank. (2018). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Washington DC: World Bank.
TangselOke. (2025). “Pemkot Tangsel Akan Buang Sampah ke TPA Bongkonol, DPRD Pandeglang Menolak.” [Online].