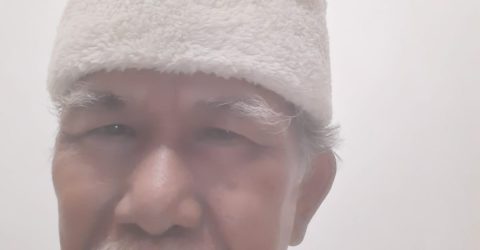(Presiden Prabowo kesal BUMN Rugi tapi Bagi-Bagi Bonus)_
Oleh MS.Tjik.NG
Bismillahirrahmanirrahim*
Pendahuluan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering disebut sebagai “anak kandung negara” yang memikul dua beban sekaligus: sebagai entitas bisnis yang harus menghasilkan laba, dan sebagai instrumen negara untuk menjalankan fungsi sosial serta penugasan strategis.
Idealnya, BUMN menjadi motor penggerak ekonomi nasional, penyangga stabilitas pasar, sekaligus sumber penerimaan negara.
Namun kenyataan di lapangan tidak selalu seindah harapan. Sejumlah BUMN mengalami kerugian besar, bahkan berulang- ulang, sehingga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: mengapa banyak BUMN rugi?
Salah satu jawaban populer dan sarkastis yang sering muncul adalah: “karena komisarisnya goblok”. Maksudnya, jabatan komisaris sering diisi oleh orang-orang yang tidak profesional, tidak ahli di bidangnya, atau bahkan hanya titipan politik.
Akibatnya, fungsi pengawasan terhadap direksi tidak berjalan optimal, strategi bisnis gagal, dan perusahaan akhirnya terjerembab dalam kerugian.
Namun apakah benar kerugian BUMN sepenuhnya disebabkan oleh “komisaris goblok”? Ataukah ada faktor lain yang lebih kompleks, seperti tekanan politik, penugasan negara yang tidak berorientasi profit, hingga tata kelola yang memang lemah?.
Artikel ini mencoba mengurai secara lebih dalam persoalan tersebut, dengan menimbang faktor manajerial, struktural, serta dinamika politik yang membentuk wajah BUMN di Indonesia.
Fungsi Komisaris dalam Struktur BUMN
Secara teori, struktur pengelolaan BUMN mengikuti prinsip tata kelola perusahaan modern (corporate governance). Ada Direksi sebagai eksekutif yang mengelola perusahaan sehari-hari, dan ada Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan serta memberikan nasihat strategis kepada direksi.
Peran komisaris sangat vital, karena mereka menjadi “penjaga gawang” agar direksi tidak keluar jalur, memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam konteks BUMN, komisaris bahkan punya tanggung jawab lebih besar karena mengelola aset publik yang nilainya triliunan rupiah.
Idealnya, anggota dewan komisaris dipilih berdasarkan kapasitas profesional, pengalaman bisnis, dan integritas. Mereka harus paham sektor industri yang digeluti BUMN tersebut—baik itu perbankan, energi, transportasi, maupun infrastruktur.
Dengan pemahaman mendalam, komisaris dapat memberikan arahan yang tepat, mengawasi strategi bisnis, serta menjadi mitra kritis bagi direksi.
Namun idealitas ini sering kali tidak terwujud dalam praktik. Banyak posisi komisaris di BUMN diisi dengan pertimbangan politik, balas jasa, atau sekadar bagi-bagi kursi kekuasaan.
Fenomena inilah yang menimbulkan stigma “komisaris goblok”, karena banyak dari mereka dianggap tidak mengerti apa-apa tentang bisnis yang diawasi.
Realitas: Titipan Politik, Nepotisme, dan Kurangnya Profesionalisme
Di Indonesia, jabatan komisaris BUMN kerap dipandang sebagai “lahan basah”. Ada beberapa realitas yang membuat kursi ini sangat diminati:
1.Gaji dan fasilitas besar
Meskipun tidak mengelola perusahaan sehari-hari, komisaris mendapat gaji dan tunjangan yang sangat tinggi. Bahkan dalam beberapa kasus, pendapatan komisaris bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
2.Jabatan prestisius
Duduk sebagai komisaris BUMN dianggap prestise, karena melekat dengan kekuasaan negara.
3.Lahan politik
Banyak komisaris berasal dari kalangan politisi atau orang dekat kekuasaan. Jabatan ini sering dianggap sebagai “hadiah” bagi pendukung politik tertentu.
Akibatnya, kompetensi sering kali bukan faktor utama dalam penunjukan komisaris. Hal inilah yang membuat banyak komisaris dianggap tidak profesional.
Mereka tidak memahami laporan keuangan, tidak bisa membaca dinamika pasar, bahkan tidak paham bisnis inti perusahaan. Fungsi pengawasan pun hanya formalitas, sebatas hadir rapat dan tanda tangan notulen.
Kasus seperti ini membuat publik mencemooh dengan istilah _“komisaris titipan”_ atau _“komisaris goblok”._
Faktor Struktural: BUMN Sebagai Alat Politik dan Sosial
Namun menyalahkan komisaris saja tentu tidak cukup. Ada faktor struktural yang juga memengaruhi kerugian BUMN, yaitu posisi ganda mereka sebagai entitas bisnis sekaligus instrumen negara.
BUMN sering diberi penugasan khusus oleh pemerintah yang secara bisnis tidak menguntungkan. Misalnya:
Menjual BBM dengan harga murah untuk stabilisasi ekonomi.
Melaksanakan proyek infrastruktur yang secara komersial belum layak.
Membiayai program sosial demi kepentingan politik pemerintah.
Dalam banyak kasus, beban penugasan ini membuat BUMN merugi. Namun kerugian itu dianggap sebagai “kontribusi sosial” kepada negara.
-888-
Studi Kasus: BUMN Rugi vs BUMN Untung
1.Garuda Indonesia
Garuda adalah contoh klasik BUMN yang berkali-kali rugi. Penyebabnya berlapis: salah urus manajemen, beban utang tinggi, intervensi politik, hingga skandal korupsi. Komisaris dan direksi sering berganti, namun perbaikan struktural tidak pernah tuntas.
2.PT Krakatau Steel
Perusahaan baja pelat merah ini mengalami kerugian bertahun-tahun akibat inefisiensi, teknologi usang, dan persaingan dengan baja impor murah. Pengawasan komisaris lemah, dan pemerintah terlalu lama membiarkan masalah berlarut-larut.
3.Telkom Indonesia
Sebaliknya, Telkom termasuk BUMN yang sukses. Sebagai perusahaan telekomunikasi, Telkom mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi digital, melakukan ekspansi bisnis, dan menghasilkan laba besar. Faktor profesionalisme direksi dan komisaris menjadi kunci keberhasilan.
4 Bank Mandiri
Lahir dari restrukturisasi krisis 1998, Bank Mandiri kini menjadi bank terbesar di Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan tata kelola yang baik dan komisaris profesional, BUMN bisa bersaing di pasar terbuka.
Analisis: Komisaris Goblok atau Sistem Rusak?
Dari uraian di atas, terlihat bahwa kerugian BUMN bukan semata-mata karena “komisaris goblok”. Memang benar, banyak komisaris tidak kompeten dan hanya titipan politik, sehingga pengawasan lemah. Namun faktor lain yang tidak kalah penting adalah sistem tata kelola yang tidak sehat.
Beberapa poin analisis:
Komisaris tidak profesional: tidak mampu memberi arahan, hanya sekadar simbol politik.
Direksi lemah atau tidak independen: sering tunduk pada intervensi politik.
Penugasan negara yang tidak profit oriented: BUMN dipaksa menjalankan proyek sosial tanpa kompensasi memadai.
Budaya birokratis dan korupsi: inefisiensi menjadi penyakit lama yang sulit diberantas.
Dengan kata lain, kerugian BUMN adalah kombinasi antara manajerial buruk (komisaris dan direksi) serta struktur kelembagaan yang tidak sehat.
-888-
Reformasi Tata Kelola BUMN
Agar BUMN tidak terus menjadi sumber kerugian, ada beberapa langkah reformasi yang perlu dilakukan:
1.Profesionalisasi penunjukan komisaris dan direksi.
Harus ada standar kompetensi yang jelas. Pengisian jabatan harus berbasis meritokrasi, bukan politik.
2 Transparansi dan akuntabilitas.
Laporan keuangan BUMN harus terbuka untuk publik, agar ada kontrol sosial.
3.Kompensasi atas penugasan negara.
Jika BUMN ditugaskan menjalankan program sosial, negara harus memberikan kompensasi yang adil.
4 Penguatan fungsi Kementerian BUMN
Kementerian harus lebih ketat dalam evaluasi kinerja komisaris dan direksi.
5.Penerapan prinsip good corporate governance (GCG)
Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness harus menjadi roh pengelolaan BUMN.
Kesimpulan
Pertanyaan apakah BUMN rugi karena “komisaris goblok” sebenarnya hanya menangkap sebagian dari persoalan. Memang benar, banyak komisaris tidak kompeten dan hanya titipan politik, sehingga pengawasan lemah.
Namun kerugian BUMN tidak bisa dijelaskan hanya dengan faktor itu. Ada struktur tata kelola yang rusak, intervensi politik yang kuat, serta penugasan negara yang sering tidak sejalan dengan logika bisnis.
Artinya, masalah BUMN lebih besar dari sekadar individu komisaris. Yang diperlukan adalah reformasi menyeluruh: profesionalisasi pengelolaan, penerapan good corporate governance, dan pemisahan jelas antara fungsi bisnis dan fungsi sosial BUMN.
Hanya dengan cara itu BUMN bisa benar-benar menjadi “pilar ekonomi nasional”, bukan sekadar sapi perah politik yang terus merugi.
والله اعلم بالصواب
C04102025, Tabik 🙏
Daftar Pustaka
Alfarizi, B. (2021). Good Corporate Governance dalam BUMN: Studi atas Fungsi Dewan Komisaris. Jurnal Manajemen & Bisnis, 18(2), 55–72.
Anggoro, A. (2019). “Komisaris BUMN dan Kepentingan Politik: Analisis Penempatan Jabatan Publik.” Jurnal Politik Indonesia, 5(1), 88–104.
Fitriani, R. (2020). Tata Kelola Perusahaan di Indonesia: Antara Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
Hidayat, T. (2022). “Mengurai Akar Masalah Kerugian BUMN: Faktor Struktural dan Manajerial.” Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 11(3), 120–136.
Kementerian BUMN Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Kementerian BUMN 2020–2021. Jakarta: Kementerian BUMN RI.
Kompas. (2022, 15 Juni). “Mengapa Banyak BUMN Merugi? Ini Penjelasan Ekonom.” Diakses dari https://www.kompas.com.
Kontan. (2021, 27 Juli). “Kementerian BUMN: Penugasan Sosial Jadi Beban Kerugian Sejumlah BUMN.” Diakses dari https://www.kontan.co.id.
Nugroho, D. (2018). Politik Ekonomi BUMN di Indonesia: Dari Orde Baru ke Reformasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
OECD. (2015). OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Paris: OECD Publishing.
Republika. (2020, 12 Oktober). “Telkom dan Bank Mandiri Jadi BUMN Paling Untung.” Diakses dari https://www.republika.co.id.
Setiawan, B. (2023). “Komisaris Titipan Politik: Dampaknya terhadap Tata Kelola BUMN.” Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 9(1), 33–47.
Tempo. (2021, 10 Mei). “Kasus Garuda Indonesia: Dari Rugi hingga Skandal Korupsi.” Diakses dari https://www.tempo.co.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
World Bank. (2020). State-Owned Enterprises: Governance and Performance in Emerging Markets. Washington, DC: World Bank.