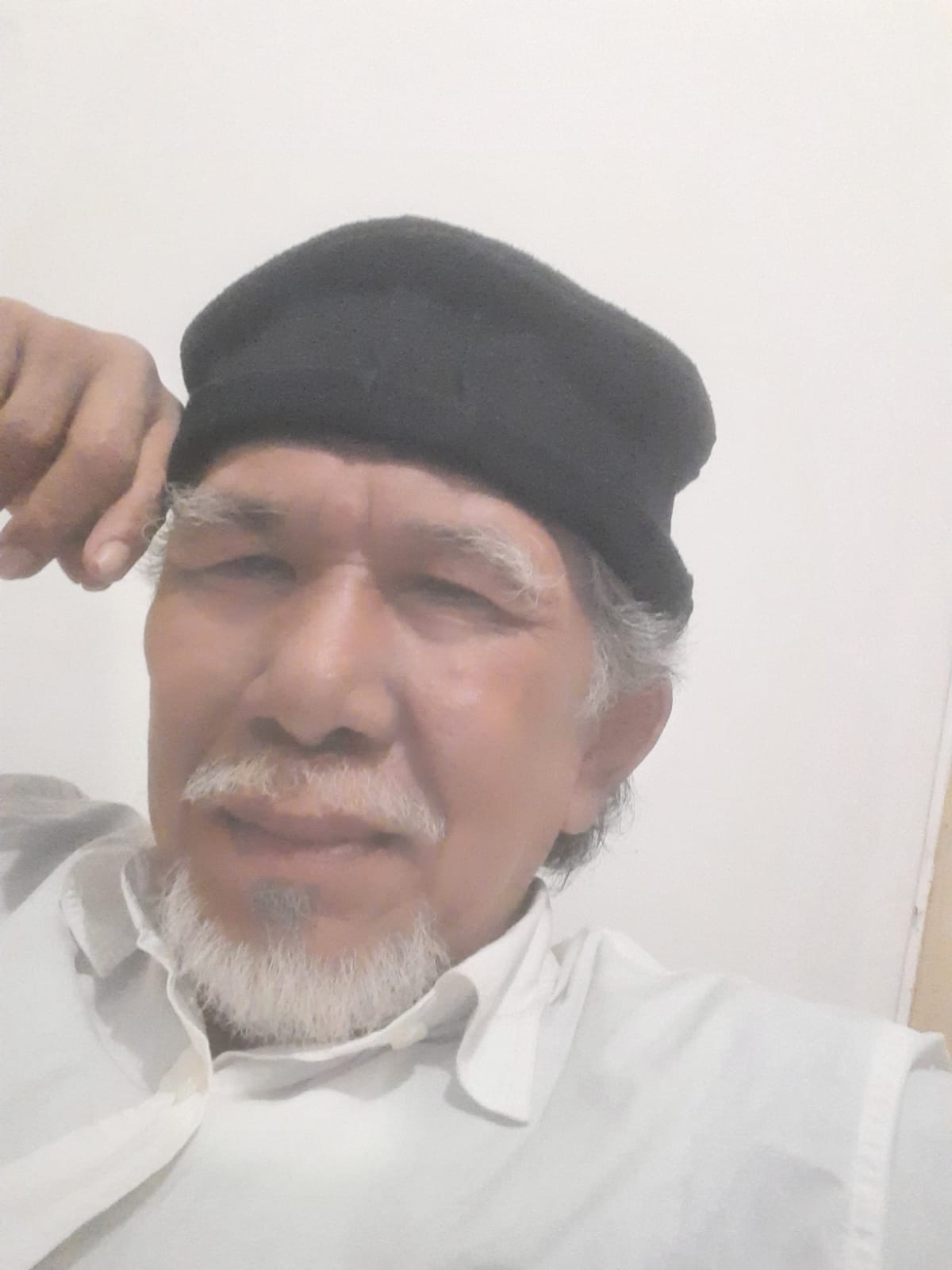MS.Tjik.NG
*Bismillahirrahmanirrahim*
_Pendahuluan_
Penjarahan dalam sejarah bangsa Indonesia bukanlah fenomena baru. Ia selalu muncul ketika ada ketidakstabilan sosial, ekonomi, maupun politik. Saat masyarakat marah, frustrasi, dan tidak melihat keadilan dari negara, penjarahan menjadi jalan ekspresi yang salah arah.
Kita melihatnya berulang: dari kerusuhan sosial di masa kolonial, gejolak politik 1965, kerusuhan Mei 1998, hingga demonstrasi 25–30 Agustus 2025 yang kembali diwarnai aksi pembakaran, perusakan, dan penjarahan toko-toko.
Namun, penjarahan massa ini sesungguhnya hanya bayangan kecil dari bentuk penjarahan yang jauh lebih besar, lebih sistematis, dan lebih merugikan: penjarahan sumber daya alam (SDA). Sejak 1965 hingga 2025, Indonesia mengalami perampasan besar-besaran atas emas, minyak, gas, nikel, timah, kayu, ikan, hingga pasir laut.
Pertanyaan besar muncul: mengapa penjarahan kecil oleh rakyat selalu ditindak tegas, sementara penjarahan besar SDA kerap dilegalkan, bahkan dianggap sebagai pembangunan?
-888-
_Penjarahan Massa dalam Konteks Sosial Politik_
1 Definisi dan Karakteristik
Penjarahan massa biasanya terjadi secara spontan, tanpa rencana, dilakukan oleh kelompok masyarakat yang marah. Sasarannya sering toko, gudang, minimarket, bahkan fasilitas publik.
2 Sejarah Singkat Penjarahan Massa di Indonesia
Mei 1998: Ribuan toko, pusat perbelanjaan, dan rumah dibakar serta dijarah. Kerugian ditaksir Rp 3 triliun.
Kerusuhan Poso (2000–2001): Konflik komunal yang juga disertai penjarahan aset ekonomi lokal.
Demonstrasi 2019–2020: Beberapa aksi mahasiswa diwarnai pembakaran halte, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan minimarket.
Demo 25–30 Agustus 2025: Sejumlah kota besar mengalami chaos, toko-toko dijarah.
3.Sosiologi Penjarahan Massa
Penjarahan oleh rakyat kecil lahir dari frustrasi sosial. Harga mahal, pengangguran tinggi, akses pendidikan dan kesehatan sulit. Ketika ada momentum chaos, mereka melampiaskannya dengan cara “merampas” yang sebenarnya merupakan simbol ketidakadilan struktural.
_Penjarahan Sumber Daya Alam (1965–2025)_
1 Awal Liberalisasi SDA (1965–1970-an)
Setelah 1965, Orde Baru membuka pintu lebar bagi modal asing. Freeport memperoleh izin eksploitasi emas dan tembaga di Papua (1967), diikuti oleh kontrak karya dengan perusahaan migas raksasa seperti Caltex dan Exxon.
2 Orde Baru: Puncak Penjarahan (1970–1998)
Kayu: Logging besar-besaran di Kalimantan dan Sumatera. FAO mencatat, Indonesia kehilangan ±1,6 juta hektar hutan per tahun pada dekade 1980-an.
Minyak dan Gas: Sebagian besar hasilnya dipakai bayar utang luar negeri.
Timah dan Nikel: Diekspor murah, rakyat tidak menikmatinya.
3 Reformasi dan Otonomi Daerah (1998–2025)
Alih-alih membaik, desentralisasi justru melahirkan “raja-raja kecil” di daerah.
Korupsi kepala daerah di sektor tambang meningkat.
Penambangan ilegal (emas, timah, nikel) makin marak.
Illegal fishing merugikan ±Rp 300 triliun per tahun (data KKP).
Kasus suap perizinan tambang jadi langganan KPK.
4.Skala Kerugian
Laporan BPK 2019 mencatat potensi kehilangan negara dari mafia tambang mencapai Rp 200 triliun per tahun. Jika dihitung sejak 1965, maka kerugian mencapai ribuan triliun rupiah.
_Membandingkan Dua Jenis Penjarahan_
Aspek Penjarahan Massa Penjarahan SDA
Skala Lokal, sesaat Nasional, sistematis
Pelaku Rakyat miskin Oligarki, korporasi
Kerugian Ratusan miliar Ribuan triliun
Dampak Trauma sosial Ekonomi-ekologi lintas generasi Reaksi Negara Cepat, represif Lemah, permisif
_Studi Kasus_
1.Freeport Papua (1967–2025)
Negara hanya mendapat royalti 1% pada awal kontrak. Sementara, kerusakan lingkungan di Mimika tak terhitung.
2.Deforestasi Kalimantan & Sumatera
Antara 1980–2000, Indonesia kehilangan 20 juta hektar hutan. Dampaknya banjir, asap kebakaran, krisis satwa langka.
3 Illegal Fishing di Laut Natuna
Kapal asing terus mencuri ikan. Laporan KKP: kerugian Rp 300 triliun per tahun.
4.Kerusuhan Mei 1998
Dibanding SDA, kerugian material penjarahan ini jauh lebih kecil, meski luka sosialnya dalam.
_Analisis Kritis_
Penjarahan massa = “api kecil” dari frustrasi rakyat.
Penjarahan SDA = “kebakaran besar” yang berlangsung puluhan tahun.
Negara represif terhadap rakyat kecil, tapi permisif terhadap elite.
Oligarki menggunakan hukum untuk melegalkan perampasan SDA.
-888-
_Penjarahan dalam Perspektif Teori_
1.Teori Strain (Merton): Kesenjangan antara harapan (akses ekonomi) dan realita (kemiskinan) → lahir penjarahan massa.
2.Teori Ketergantungan: Indonesia terjebak menjadi pemasok bahan mentah bagi dunia industri.
3.Ekonomi Politik: SDA menjadi sumber akumulasi kapital bagi elite, bukan rakyat.
_Jalan Keluar_
Transparansi tata kelola SDA.
Penegakan hukum tanpa pandang bulu (baik rakyat kecil maupun oligarki).
Restorasi lingkungan dan pengelolaan SDA berbasis rakyat.
Pendidikan politik agar rakyat sadar siapa “penjarah sebenarnya”.
_Kesimpulan_
Penjarahan yang dilakukan rakyat saat demonstrasi hanyalah riak kecil. Sementara penjarahan SDA sejak 1965 adalah tsunami besar yang meluluhlantakkan bangsa.
Ironisnya, penjarahan kecil dihukum berat, sementara penjarahan besar sering dilegalkan dan bahkan dipuji sebagai investasi.
Bangsa Indonesia harus berani melihat kenyataan: selama enam dekade, kita lebih sibuk menghukum rakyat kecil daripada menghentikan penjarah besar.
Bukankah Dewi keadilan
dengan mata tertutup sembari memegang pedang terhunus. Melambangkan pedang keadilan tajam ke atas dan tajam pula kebawa. Itu artinya keadilan harus ditegakkan alias tidak pandang bulu, kedudukan dan status sosial.
والله اعلم بالصواب
C31082025, Tabik🙏
Referensi :
Aspinall, E. (2013). Indonesian Politics and Resource Extraction.
Ross, M. (2001). Timber Booms and Institutional Breakdown in Southeast Asia.
Hadiz, V. (2004). Decentralization and Democracy in Indonesia.
Kompas, Tempo, Mongabay, Walhi (berbagai laporan investigatif).
Laporan KKP (2015–2023).
BPK RI (2019, 2021).